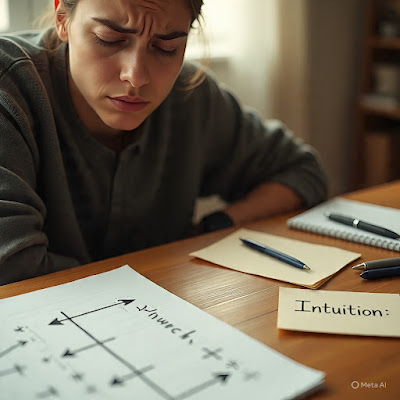Belakangan ini, kata “authentic” sering banget dipake orang. Banyak yang bangga bilang, “Gue tuh orangnya authentic, ngomong apa adanya, gak bisa munafik.” Biasanya ujung-ujungnya mereka jadi tipe orang yang mulutnya gak ada filter—semua yang dipikir langsung keluar.
Pertanyaannya: emang gitu ya cara jadi authentic? Dan kalau kita milih buat gak ngomong semua isi hati, otomatis kita jadi munafik?
Authentic Itu Apa Sih?
Authentic itu intinya lo hidup selaras sama apa yang lo rasain, lo pikir, dan lo lakuin. Gak pura-pura jadi orang lain, gak bohong sama diri sendiri.
Tapi authentic itu bukan berarti semua isi hati harus dilontarin mentah-mentah. Kalau lo bete terus langsung marah-marah tanpa mikirin efeknya ke orang lain, itu bukan “authentic”—itu ga ada filter.
Authentic itu tentang jujur, tapi juga sadar konteks sosial. Lo tetap jadi diri sendiri, tapi lo pilih cara nyampeinnya biar lebih relate ke orang lain.
Munafik Bukan Cuma Soal Menyembunyikan Perasaan
Banyak orang suka salah kaprah. Katanya kalau kita nahan omongan berarti kita munafik. Padahal, munafik itu lebih ke lo ngomong atau ngelakuin sesuatu yang bertentangan total sama isi hati lo. Biasanya demi keuntungan pribadi atau sekadar pencitraan.
Contoh gampang: lo kesel banget sama bos lo, tapi depan dia lo muji-muji kayak fangirl. Itu baru munafik.
Kalau lo cuma nyaring cara ngomong biar gak nyakitin orang lain, itu bukan munafik. Itu namanya kedewasaan dalam komunikasi.
Menjaga Perasaan Itu Skill
Menjaga perasaan orang bukan berarti lo palsu. Justru itu skill sosial yang penting. Lo sadar orang lain juga punya emosi, jadi lo atur cara ngomong biar pesannya nyampe tanpa bikin luka yang gak perlu.
Analoginya kayak nyuapin anak kecil. Lo gak mungkin kasih dia cabe rawit bulat-bulat, kan? Lo pilih makanan yang bisa dia cerna. Sama juga pas ngomong—lo tetap jujur, tapi dikemas biar orang lain bisa nerima.
Contoh Real: Temen yang Sering Telat
- Blak-blakan mentah: “Lo ngeselin banget sih, telat mulu. Gue ilfil sama lo.” → Authentic, tapi nyakitin.
- Pura-pura santai: “Santai aja kok, gue seneng nungguin lo,” padahal lo gondok. → Nah ini baru munafik.
- Balance: “Bro, gue agak keganggu kalau sering nungguin. Bisa coba lebih on time gak next time?” → Authentic, considerate, gak munafik.
Authentic + Considerate = Kedewasaan
Jadi intinya lo bisa banget kok jadi authentic, considerate, dan gak munafik di saat yang sama. Lo tetap jujur sama diri sendiri, tapi lo juga mikir cara terbaik buat nyampein ke orang lain.
Ini yang namanya kedewasaan emosional. Lo bukan cuma ngomong “gue jujur apa adanya,” tapi juga “gue jujur dengan cara yang orang lain bisa terima.”
Penutup
Nyaring omongan itu bukan berarti lo palsu. Jaga perasaan juga bukan tanda lo munafik. Malah, di situlah seni hidup bareng orang lain—nemuin titik tengah antara jujur sama diri sendiri, empati sama orang lain, dan konsistensi sama prinsip.
Authentic itu ibarat kopi hitam asli. Tapi cara nyajiinnya bisa beda-beda: panas, dingin, pakai gula, atau gak. Selama rasanya tetap kopi, lo masih authentic.